Thailand dan Myanmar dalam Pusaran Kuasa Militer
- P. Lintang Mulia

- Mar 9, 2021
- 8 min read
Updated: Aug 13, 2021
Thailand dan Myanmar memang secara historis saling bertikai di abad ke-17 hingga 18 antara Kerajaan Burma dan Ayutthaya, dan mereka juga mulai memperlihatkan kekuatan militernya masing-masing. Terlepas dari pertikaian tersebut, di abad ke-20 mereka sama-sama merupakan negara yang menggunakan militer sebagai komponen utama dalam kancah perpolitikannya, dengan tujuan untuk "menjaga kestabilan negara", ataupun melindungi negara dari berbagai ancaman.
Awal Mula
Thailand yang pada dekade 1930 berada dibawah kekuasaan Raja Rama VII, menjadi saksi bisu kudeta yang dilakukan oleh kelompok Khana Ratsadon (Partai Rakyat), yang dua pimpinannya adalah Pridi Bhanomyong -seorang pengacara muda, dan Mayor Plaek Phibunsongkram atau Phibun -pimpinan perwira muda, pada 1932. Melalui kudeta ini, kekuasaan Raja Rama VII berubah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, sehingga jalan bagi militer untuk memimpin negara pun terbuka setelah Phraya Phahon -Kepala Angkatan Darat Siam, diangkat sebagai Perdana Menteri pada 1933. Dalam kabinet Phraya Phahon, posisi Menteri Pertahanan juga diisi oleh Phibun, yang nantinya naik sebagai Perdana Menteri di tahun 1938, merangkap panglima tertinggi Thailand hingga masa Perang Dunia Kedua.

Sementara di Burma, kudeta baru dimulai pada 1962 dengan keberhasilan Jenderal Ne Win menyingkirkan Perdana Menteri U Nu. Ia menganggap pemerintahan U Nu berbahaya bagi nasionalisme Burma, karena menyebabkan perpecahan diantara kalangan etnis minoritas. Dengan kudeta ini, Ne Win berhasil membawa Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Burma) sebagai komponen perpolitikan, yang masih bertahan dalam pemerintahan Myanmar hingga masa kini. Sekaligus menerapkan sistem kekuasaan otoriter, yang nyatanya belum mampu mengangkat kesejahteraan dan perekonomian rakyat Myanmar hingga 1988. Lebih daripada itu, Ne Win juga memerintahkan militer untuk menangkap sejumlah kelompok etnis seperti Shan, Mon, dan Karen.
Merebut Takhta
Kedua kudeta tersebut merupakan batu loncatan bagi militer untuk memasuki pusaran perpolitikan negara, bahkan saling mengkudeta satu sama lain dalam beberapa kasus. Diantaranya seperti Kudeta Thailand 1957, dimana Jenderal Sarit mengkudeta Phibun sebagai upaya koreksi terhadap demokrasi Thailand, agar lebih mengakar ke nilai bangsa Thai. Beberapa Perdana Menteri setelah Sarit pun seperti Marsek Thanom Kittikachorn muncul dari kalangan militer, tetapi karena kepemimpinannya mendapat oposisi dari kalangan mahasiswa, Raja Rama IX pun memutuskan untuk mengasingkan Thanom pada 1973.

Dalam masa tersebut, Thailand menyadari bahwa pengaruh Perang Dingin berupa ideologi kiri akan masuk melalui dampak Perang Vietnam dan Perang Saudara Kamboja, sehingga organisasi paramiliter "Krating Dhaeng" berkembang untuk melawan siapapun yang dianggap "kiri". bahkan organisasi ini juga dituding sebagai salah satu dalang dari peristiwa Universitas Thammasat 1976, yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Setahun setelahnya Thailand kembali berada dalam kuasa militer di bawah PM Jenderal Kriangsak Chamanan, yang digantikan oleh PM Prem Tinsulanonda pada 1980 hingga 1988.

Pada 1991, sempat terjadi kudeta untuk ke-18 kalinya dari pihak militer yang dilakukan oleh Jenderal Sunthorn Kongsompong dan Jenderal Suchinda Kraprayoon, menggulingkan PM Chatichai Choonhavan dengan tujuan untuk "mengembalikan dan menguatkan demokrasi melalui amandemen undang-undang". Walaupun setelah kudeta tersebut diangkat PM Anand Panyarachun dari kalangan sipil, tahun 1992 Thailand mengadakan Pemilihan Umum yang dimenangkan oleh Jenderal Suchinda.

Terpilihnya sang Jenderal memicu amarah 200 ribu orang, yang berdemonstrasi untuk menuntut amandemen konstitusi Thailand, meniadakan jam malam, sekaligus menuntut mundurnya Suchinda. Dari banyaknya elemen masyarakat yang melakukan demo pada 17 Mei 1992, salah satunya adalah Mayjen (Purn.) Chamlong Srimuang, pimpinan partai Palang Dharma. Militer pun kembali dilibatkan pada 19 Mei untuk meredam demonstrasi ini, yang berakibat jatuhnya korban jiwa saat pembubaran demonstran, sehingga Raja Rama IX pun memanggil Jenderal Suchinda dan Chamlong, pimpinan demonstrasi untuk berdialog. Hasil yang dicapai berupa dihentikannya aksi baik dari demonstran yang dipimpin Mayjen (Purn.) Chamlong, dan ditariknya kembali pasukan militer ke barak mundurnya Jenderal Suchinda, dan kembalinya Anand sebagai Perdana Menteri.

Sementara itu di Burma, pada tahun 1988 telah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran (Aksi 8888), dengan tujuan menggulingkan pemerintahan diktator Jenderal Ne Win. Dalam satu waktu, pemerintahan Burma pun terpecah belah setelah mundurnya Ne Win pada bulan September, akan tetapi pihak militer kembali membentuk Dewan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Walaupun nama Burma telah berganti menjadi Myanmar setahun setelahnya, masalah pun terus terjadi antara pihak militer. Jenderal Saw Maung pun yang menggantikan Ne Win, belum berhasil mengatasi masalah ekonomi di Myanmar seiring dengan penyatuan seluruh etnis baik Shan, Mon, ataupun Karen kedalam etnis "Burma", dimana kerap terjadi pertikaian bersenjata sepanjang dekade 1990.
Di tengah rezim militer ini, Myanmar pun juga sukses mengadakan Pemilu 1990 yang dimenangkan NLD (Liga Nasional Demokrasi), dengan pimpinannya Aung San Suu Kyi. Tetapi hasil pemilu dibatalkan secara sepihak oleh militer, dan Suu Kyi pun ditahan, sehingga rezim militer tetap berjalan hingga Saw Maung digantikan oleh Jenderal Than Shwe, yang memimpin rezim hingga 2011.
Militer Negeri Pagoda dalam Kancah Abad 21
Thailand
Dalam 15 tahun terakhir, kakak beradik Shinawatra -Thaksin dan Yingluck, menjadi sasaran kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014. Pada 2006, PM Thaksin digulingkan oleh militer setelah dua tahun didemo oleh "Kaus Kuning", pendukung faksi kerajaan, yang mengecam pemerintahannya akibat tudingan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Sedangkan kubu Kaus Merah -Pendukung Thaksin, melakukan demo pada Maret hingga Mei 2010 untuk menentang kepemimpinan PM Abbhisit Vejajiva, yang didukung oleh faksi kerajaan. Sebanyak 91 orang tewas dan 2000 terluka dari pihak Kaus Merah saat mereka berdemonstrasi menentang sang perdana menteri.
Sementara bagi Yingluck, Partai Pheua Thai yang ia pimpin dengan dorongan dari Thaksin berhasil memenangkan Pemilu 2011, dan secara praktis ia pun diangkat sebagai PM menggantikan Abhisit Vejjajiva. Sekali lagi, Kaus Kuning pun kembali turun ke jalan berdemo menentang Yingluck karena dianggap nepotisme, dan korban jiwa pun kembali jatuh pada November 2013 hingga Mei 2014 akibat tindakan aparat, ataupun diserang kubu Kaus Merah. Oleh sebab itu, hal ini menjadi justifikasi bagi pimpinan militer Thailand untuk sekali lagi melakukan kudeta, yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-Ocha, Kepala AD Thailand

Naiknya Prayuth sebagai Perdana Menteri memicu berbagai kontroversi dengan sifatnya yang anti kritik, mereka juga mengesahkan Konstitusi 2017 yang melemahkan berbagai partai politik, dan memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Hal ini memicu peningkatan ketidakpuasan rakyat Thailand di tahun 2019 hingga 2020, yang juga mengkritik sikap keluarga kerajaan yang kerap hidup bermewahan, sehingga mereka mendesak reformasi monarki sekaligus menuntut PM Prayuth agar mundur. Sejak Februari 2020, ratusan ribu orang turun ke jalan walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19, dan aparat pun bertindak dengan segera menangkap beberapa figur yang dianggap sebagai provokator demonstrasi. Penangkapan ini juga diduga sebagai bentuk penegakan hukum Pasal 112 Konstitusi Thailand, yang mengecam segala kritik terhadap kerajaan.

Walaupun korban luka mulai berjatuhan, PM Prayuth pun tetap menolak untuk mundur, dan menyatakan bahwa ia segera mencari solusi terbaik bersama parlemen untuk menyelesaikan masalah ini. Berlawanan dengan pernyataan ini, protes masih berlanjut sejak bulan Oktober dan masih terus berlangsung walau tidak secara kontinu. Bahkan terhitung sejak Januari 2021, 55 orang telah ditangkap karena melanggar Pasal 112 UU Thailand. Dan sejak demonstrasi bermula, akses sosial media pun juga mulai dibatasi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Myanmar

Sementara di Myanmar, berbagai gerakan demokratis yang dilakukan NLD terus ditekan oleh militer, sehingga memicu terjadinya Revolusi Saffron yang dimotori oleh mahasiswa angkatan 1988, dan sejumlah bhiksu pada 2007. Pada 2010, tindakan militer mulai melunak dan Aung San Suu Kyi dibebaskan, dan NLD pun diizinkan kembali untuk melakukan aktivitas politiknya, seiring dengan bergantinya pemerintahan dari junta militer ke pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein. Sang presiden pun melakukan serangkaian reformasi politik, HAM, dan ekonomi untuk memperbaiki kondisi negara. Dengan dukungan untuk demokrasi dari rakyat, NLD pun berhasil memenangkan pemilu pada 2012 dan 2015, yang berujung pada pengangkatan Aung San Suu Kyi Penasihat Negara, setingkat perdana menteri pada 2016
Dibalik kebebasan berdemokrasi tersebut, militer masih tetap memegang kendali atas keberadaan etnis minoritas di Myanmar, dan kini salah satunya termasuk Rohingya, bukan hanya Shan, Mon Kachin, ataupun Karen. Antara militer dan pihak Rohingya sendiri, masih terlibat kontak senjata hingga 2020, yang dimana pada 2012 sebanyak 192 orang tewas akibat kekerasan dari pihak militer, dan ratusan ribu mengungsi sebagai dampaknya. Pada Oktober 2016, Pasukan Pembebasan Arakan Rohingya (ARSA) menyerang pos perbatasan milik kepolisian di negara bagian Rakhine, dan sebagai imbasnya militer Myanmar pun menindak semua gerakan ARSA secara represif, termasuk menindak etnis Rohingya yang tidak ikut terlibat dalam baku tembak tersebut.

Sejak peristiwa ini, pemerintah dan militer telah membatasi akses bagi para jurnalis, dan relawan sosial yang akan masuk ke negara bagian Rakhine. PBB pun juga menyerukan bahwa situasi yang dialami oleh etnis ini sebagai "mimpi buruk bagi kemanusiaan dan hak asasi manusia", sehingga pada Februari 2017 UNHRC memutuskan untuk mengirimkan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dalam menyelidiki kasus di Rakhine. Namun demikian Aung San Suu Kyi menolak proposal pengiriman TGPF, dan bersikap acuh tak acuh terhadap saran intervensi dari pihak internasional, bahkan sejak Agustus 2017 ribuan korban jiwa harus meregang akibat represi militer.
Empat tahun sekiranya berlalu, pemerintah Myanmar seolah gelap mata atas apa yang terjadi di Rakhine, ataupun terhadap beberapa etnis minoritas di Myanmar dalam waktu puluhan tahun. Di lain sisi, militer kali ini mengambilalih kekuasaan NLD dan menangkap sejumlah petinggi pemerintahan Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing ini, merupakan bentuk ketidakpuasan militer terhadap kemenangan NLD pada Pemilu 2020, yang semakin memudarkan pengaruh militer di Myanmar. Lebih daripada itu, pihak militer yang selama ini telah menjadi bagian pemerintah melihat pengaruhnya mulai memudar akibat demokratisasi Myanmar, terlepas dari berbagai represi mereka terhadap berbagai etnis minoritas di Myanmar.


Demonstrasi besar pun muncul walau semua akses komunikasi baik telepon ataupun internet dibatasi oleh junta militer, jutaan orang mampu berkumpul dari berbagai kalangan untuk melakukan pembelotan sipil dan mogok kerja. Kali ini, semua etnis pun bersatu baik etnis Burma, Shan, Karen, ataupun Rohingya untuk melawan kudeta militer. Hingga minggu pertama bulan Maret 2021 sebanyak 60 orang tewas di tangan militer, dan ratusan terluka akibat tindakan represif militer untuk menertibkan pendemo, dengan peluru tajam dan gas air mata.
Bagi etnis Burma, kudeta ini merupakan titik balik bagi mereka untuk menyadari, bahwa propaganda mengenai etnis Rohingya yang digaungkan oleh militer dan pemerintah sudah tidak berlaku. dan kini mereka mulai sadar bahwa militer juga dapat bertindak kejam pada mereka. Dan hal tersebutlah yang juga memotivasi mereka untuk bersatu dengan etnis lain, untuk melawan kudeta
Baik Thailand ataupun Myanmar, memakai militer sebagai komponen utama aksi kudeta dengan dalih kestabilan negara. Walaupun demokrasi diberikan sedikit nafas dalam perjalanannya, militer akan tetap bertindak jika mereka melihat demokrasi sebagai ancaman kestabilan negara, ataupun ancaman bagi institusi mereka. Dalam tipologi militer Eric Nordlinger, keduanya termasuk kedalam tipologi praetorian yang melakukan kudeta, sebagai cara untuk mendominasi pemerintahan.
Tetapi dalam memerintah, Thailand mengarah kepada tipe ruler dengan pimpinan kudeta yang beralih menjadi perdana menteri, dan menjadi sebuah simbol negara karena juga mendapat dukungan dari kaum royalis (pendukung Kerajaan Thai). Sementara itu Myanmar dalam 10 tahun terakhir militernya berada dalam tipe guardian, dimana mereka tetap memegang kontrol keamanan dibalik berkuasanya NLD, dan kini nampak kembali ke tipe ruler layaknya pra-2011, dengan represi yang terjadi belakangan ini sebagai upaya koreksi atas ketidakpuasan terhadap kemenangan NLD.
DISCLAIMER: Artikel ini ditulis dengan tujuan edukasi dan pengetahuan. Penulisan dalam artikel ini juga bersifat netral, dengan tidak mengesampingkan salah satu pihak atau mendukung salah satu pihak.
Referensi:
Buku
Tarling, Nicholas. (1994). The Cambridge History of Southeast Asia. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge
The Asia Foundation. (2017). The State of Conflict and Violence in Asia. Bangkok: The Asia Foundation
Jurnal
Farelly, Nicholas. (2013). Why democracy struggles: Thailand's elite coup culture, Australian Journal of International Affairs, 67 (3), 281-296
Kipgen, N. (2016). Militarization of Politics in Myanmar and Thailand. International Studies, 53(2), 153–172.
Mérieau, E. (2019). Thailand in 2018: Military Dictatorship under Royal Command. In D. Singh & M. Cook (Eds.), Southeast Asian Affairs 2019 (pp. 327-340). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Nilasari, Y. U. (2016). Proses Perubahan Politik di Myanmar: Menuju Demokrasi melalui Pemilihan Umum FORUM, 41(1), 29-33
Perlmutter, Amos. (1969). The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities. Comparative Politics, 1 (3), 382-404.
Laporan Penelitian
Selth, Andrew. (2016). Myanmar Armed Forces and the Rohingya Crisis. Washington DC: United States Institute of Peace
Artikel
Charney, Michael W. (3 Februari 2021). Myanmar coup: how the military has held onto power for 60 years. The Conversation, https://theconversation.com/myanmar-coup-how-the-military-has-held-onto-power-for-60-years-154526 (Diakses pada 3 Maret 2021)
El-Shimy, Y. (2016). A Model of Praetorian States, Harvard Kennedy School
Goldman, Russel. (4 Maret 2021), Myanmar Protest, Explained. New York Times, https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html (Diakses Pada 4 Maret 2021)
Gunia, Amy (8 Februari 2021). Rohingya Activists Are Hoping That the Coup in Myanmar Will Be a Turning Point for Their Struggle. Time, https://time.com/5936604/myanmar-coup-rohingya/ (Diakses 3 Maret 2021)
Sasipornkarn, E. (19 November 2020). Thailand Pro-democracy protesters resilient amid violent crackdown. Deutsche Welle, https://www.dw.com/en/thailand-pro-democracy-protesters-resilient-amid-violent-crackdown/a-55662875 (Diakses pada 5 Maret 2021)




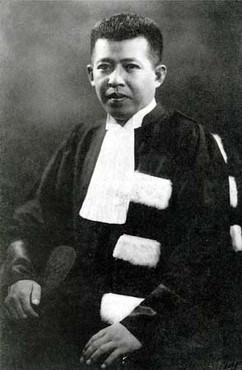






Comments